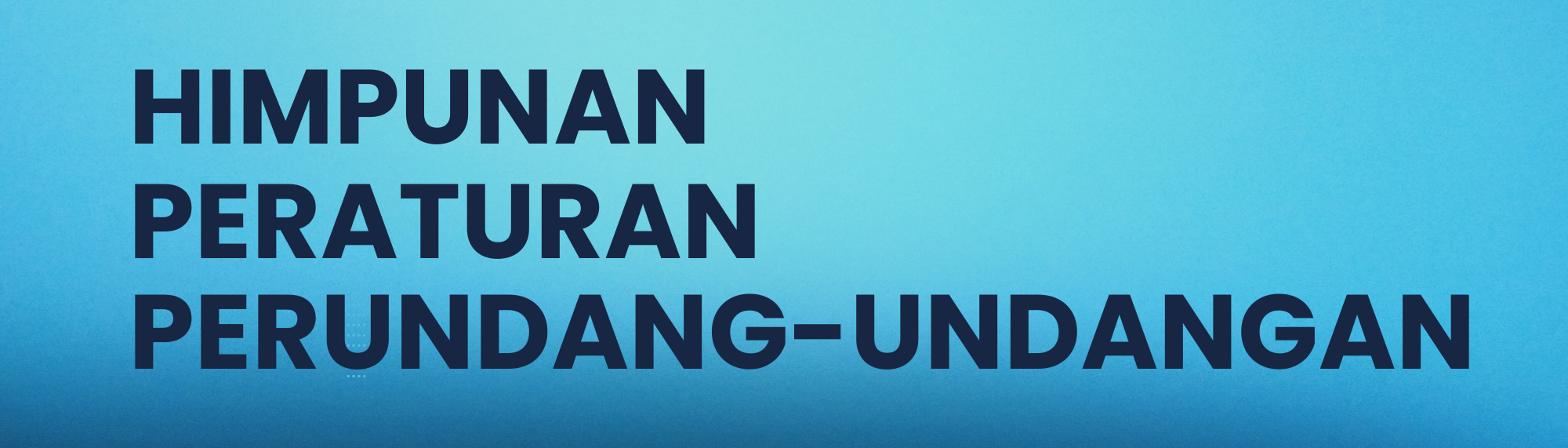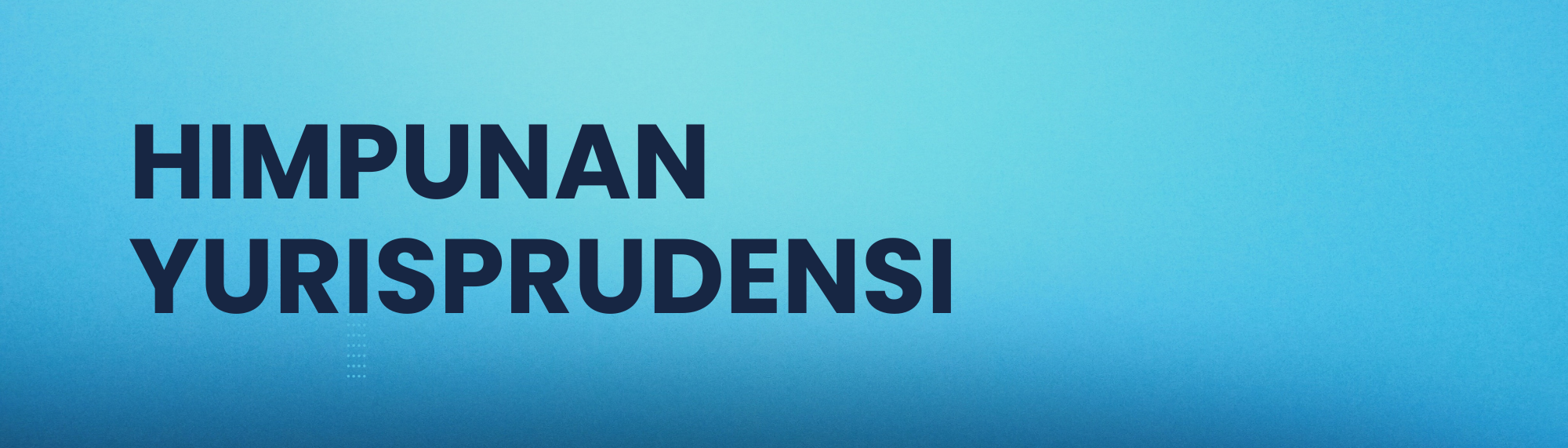Salah satu pengertian Hukum Tata Negara yang banyak digunakan di Indonesia adalah bahwa hukum tata negara adalah seperangkat aturan yang mengatur dan mengatur organisasi, hubungan, dan interaksi lembaga-lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal. Namun definisi alternatif yang sering dikemukakan di Indonesia adalah definisi Oppenheim dan Van Volenhoven yaitu hukum tata negara sebagai hukum negara-negara dalam mode hiatus.
Sebagai sebuah organisasi, Indonesia adalah negara Republik berdasarkan kedaulatan rakyatnya. Tujuan utama negara adalah:
- melindungi seluruh rakyat Indonesia;
- memajukan kesejahteraan umum rakyat;
- untuk meningkatkan standar pendidikan, dan
- berkontribusi dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk memenuhi tujuan ini Republik Indonesia telah mengadopsi seperangkat prinsip dasar yang dikenal sebagai Pancasila. Pancasila secara sederhana berarti lima prinsip. Prinsip-prinsip ini adalah:
- kepercayaan pada satu Tuhan;
- kemanusiaan yang adil dan beradab;
- Persatuan Indonesia;
- sosialisme yang dipimpin oleh kebijaksanaan dengan konferensi/perwakilan,
- keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semua asas tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar dan dapat dipertimbangkan dalam hal penafsiran undang-undang. Namun demikian, sebagian besar substansi UUD tersebut terdapat di dalam Batang Tubuh atau Isinya. Isinya memuat rangkaian ketentuan yang dapat dikatakan menetapkan norma hukum dasar masyarakat Indonesia. Konstitusi pertama hanya terdiri dari 37 Pasal, 2 Ketentuan Tambahan, dan 2 Ketentuan Peralihan. Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa hanya Parlemen yang dapat mengamandemen Konstitusi dan menetapkan aturan yang sangat spesifik yang mengatur bagaimana amandemen ini harus diberlakukan.
Amandemen konstitusi di Indonesia telah melalui beberapa fase yang berbeda dan dapat diidentifikasi. Pada mulanya Undang-Undang Dasar yang dirancang untuk tujuan kemerdekaan Indonesia diperkenalkan dan berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda yang berada di bawah naungan Pemerintah Indonesia pada masa kemerdekaan. Dalam kurun waktu 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 Terjadi masa perubahan dan perubahan di Indonesia yang mengakibatkan Deklarasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari persatuan sebelumnya dan berlakunya UUD 1950. UUD 1950 merupakan rancangan awal UUD baru yang sedang dikembangkan oleh Konstituante. Pemberlakuan UUD 1950 bersifat sementara karena Konstituante tidak pernah mampu menyelesaikan penyusunan UUD baru dan bahkan dibubarkan oleh mantan Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959 karena kegagalan ini. Pembubaran Konstituante termasuk penerapan kembali UUD 1945.
Pada masa Kepresidenan Presiden Soeharto, segala amandemen terhadap Isi UUD secara tegas dilarang. Konstitusi untuk semua tujuan intensif telah mengambil status sebagai teks 'suci' yang tidak membutuhkan amandemen apa pun. Lebih lanjut, siapa pun yang menuntut atau bahkan menyarankan agar UUD diubah, menjadi korban kebijakan pemerintah Soeharto yang menyatakan segala penentangan atau aktivisme untuk perubahan musuh Negara yang harus dilenyapkan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kemakmuran. Sifat sakral teks Konstitusi berhenti pada pengunduran diri Soeharto dari Kepresidenan pada 20 Mei 1998 dengan amandemen yang datang secara berkala. Amandemen pertama selesai pada Oktober 1998, seri kedua amandemen selesai pada Oktober 1999, seri ketiga selesai pada Oktober 2000, dan seri keempat selesai pada Oktober 2001.
Menurut Undang-Undang Dasar Indonesia, badan negara sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:
- Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat);
- Presiden;
- Menteri;
- Mahkamah Agung (Mahkamah Agung);
- Mahkamah Konstitusi (MK);
- Komisi Yudisial (Komisi Yudisial);
- Bank pusat;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Daerah); dan
- Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah).
Jika badan-badan Negara ini dilihat dari pembagian kekuasaan, maka MPR adalah badan konstitutif, DPR dan DPD badan legislatif, Presiden, Menteri, Bank Sentral, dan Pemerintah Daerah adalah badan eksekutif, dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif.
Badan-badan dan lembaga-lembaga Negara lainnya akan diatur dan diatur oleh jenis-jenis hukum tambahan lain dari Konstitusi.
Hukum tambahan ini tidak dapat digolongkan sebagai sumber hukum tata negara. Namun, penting untuk diakui bahwa sebagian besar undang-undang terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan mekanisme yang diatur dalam Konstitusi. Beberapa di antaranya yang lebih signifikan antara lain UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota untuk DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.
Hak Asasi Manusia di Indonesia dipandang sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini harus dihormati, dihormati, dan dilindungi oleh negara dan hukumnya, pemerintah, dan warga negaranya. Beberapa sumber hukum yang berperan penting dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Perubahan Kedua, khususnya Pasal 28 A-J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak.
Hukum kewarganegaraan Indonesia telah mengalami beberapa fase perkembangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan di Indonesia adalah ius soli atau kewarganegaraan yang ditentukan oleh tempat kelahiran orang tersebut. Artinya a) semua keturunan Belanda baik yang lahir di Indonesia maupun yang telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum tanggal 27 Desember 1949 diberi kesempatan untuk memilih menjadi warga negara Republik Indonesia yang baru, b) penduduk asli Indonesia yang memenuhi syarat atau pemegang kewarganegaraan Belanda yang tinggal di Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia, dan c) orang Arab dan Tionghoa yang tinggal di Indonesia dan yang tergolong warga negara Belanda di Indonesia juga diberikan kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia.
Asas kewarganegaraan ini berubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan diberlakukannya ius sanguinis atau kewarganegaraan berdasarkan hubungan darah. Namun berdasarkan kesepakatan Sonario-Chou setiap keturunan Tionghoa warga negara Indonesia berhak memilih dan atau tetap menjadi warga negara Indonesia. Orang asing dapat menjadi warga negara Indonesia dengan salah satu dari dua cara; yaitu, dan permintaan resmi atau Negara memberikan kewarganegaraan atas dasar semacam kepentingan Negara untuk melakukannya atau kontribusi yang signifikan yang diberikan oleh individu asing ke Indonesia.
Referensi
- https://www.aseanlawassociation.org/