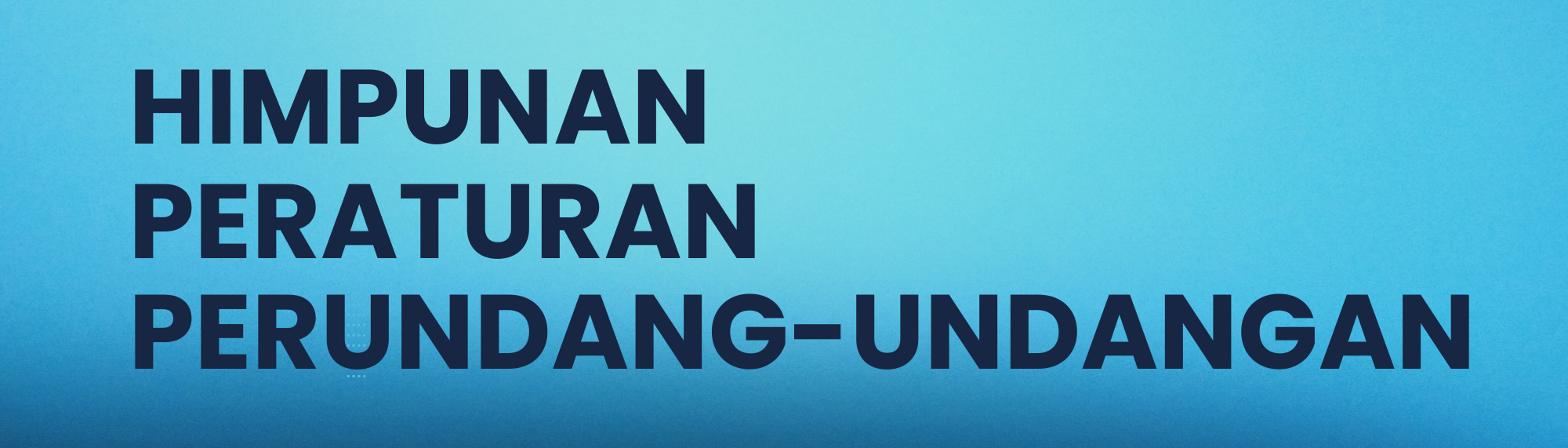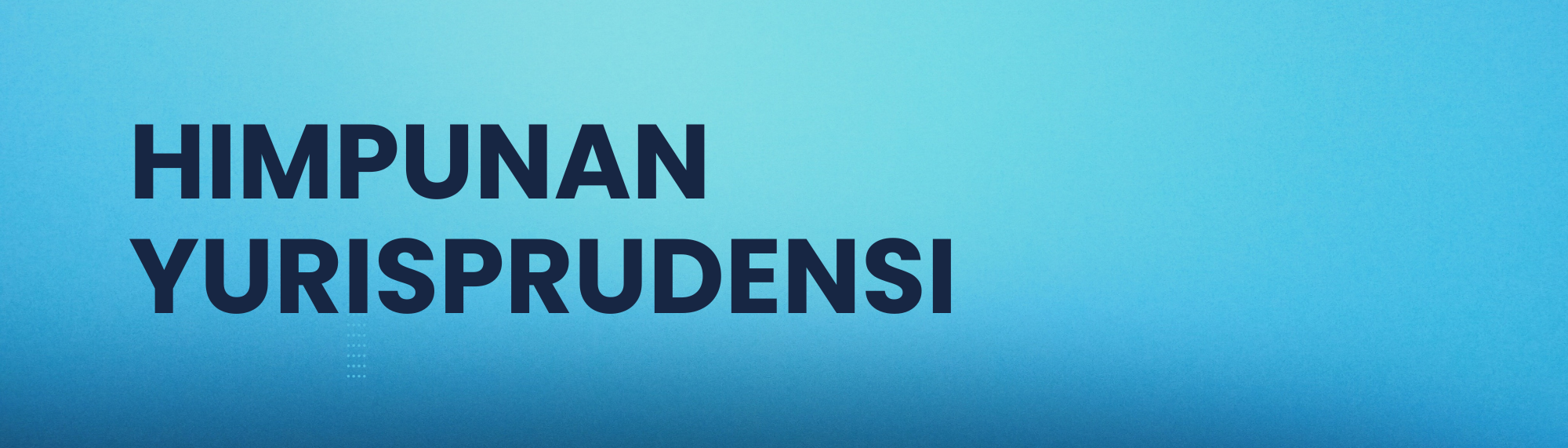Pengertian Politik Hukum
Menurut Mahfud MD politik hukum adalah ”legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara”
Ruang Lingkup Politik Hukum
- Pembentukan hukum ;
- Penerapan hukum ; dan
- Penegakan hukum
Kajian Politik Hukum
- Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan
- Latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya atas lahirnya produk hukum
- Dampak pemberlakuan produk hukum
Fungsi Politik Hukum
Salah satu fungsi politik hukum adalah menciptakan batasan yang harus dipatuhi oleh para penguasa ketika hendak membentuk produk hukum. Pedoman politik hukum nasional di antaranya adalah cita-cita bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan bagi segenap bangsa.
Relasi Koheren Antara Hukum dan Kekuasaan Politik
Perkembangan hukum kontemporer menimbulkan kecenderungan untuk memberlakukan UU sebagai perwujudan hukum positif tertulis. Dalam dinamikanya, para penganut positivisme hukum berusaha membersihkan hukum dari anasir-anasir lain (pure theory of law), termasuk anasir politik. Hal tersebut karena para penganut aliran positivisme hukum sangat mengagungkan hukum tertulis sebagai sumber kebenaran yang bersifat formal dan prosedural. Namun, hukum akan selalu memerlukan kekuasaan negara agar memiliki daya pengikat yang memaksa subjek hukum untuk menaatinya. Kekuasaan negara atau dapat juga diartikan dengan kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan tujuan para pemangku jabatan. Secara historis, tidak jarang kita menyaksikan hukum diselewengkan demi mempertahankan dan merebut kekuasaan.
Politik hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kajian kritis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang tujuan produk hukum berdasarkan relasi antara politik, hukum, dan produk hukum. Salah satu fungsi politik hukum adalah agar terciptanya batasan yang harus dipatuhi oleh para penguasa ketika hendak membentuk produk hukum sesuai dengan konsep negara hukum. Pedoman politik hukum nasional di antaranya adalah cita-cita bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan bagi segenap bangsa. Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwasanya sistem dan metode pembentukan hukum harus menjadikan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas. Hal tersebut karena pembangunan hukum dan pembangunan nasional memerlukan UU dan segala proses pembentukannya–perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan–untuk menjabarkan dan menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945“) serta menjadi jembatan bagi pembuatan dan pemberlakuan peraturan pelaksana di bawahnya. Akan tetapi, Rekapitulasi Pengujian UU MK memperlihatkan fakta bahwa jumlah pengujian UU cenderung bertambah setiap tahunnya. Jumlah perkara pengujian UU pada tahun 2022 menyentuh angka 143, naik sejumlah 22 angka dari tahun sebelumnya. Sementara itu, baru sekitar setengah tahun berjalan, jumlah pengujian UU pada tahun 2023 telah mencapai angka 81.[1] Data tersebut menandakan masih eksisnya kecacatan pada UU, baik dari segi materiel maupun segi formil.
Merujuk kepada Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, proses pembahasan hingga persetujuan suatu UU di Indonesia dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR“) bersama dengan presiden.[2] Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (“DPD“) sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah turut terlibat dalam tahapan perencanaan dan pembahasan apabila Rancangan Undang-Undang (“RUU“) itu berkaitan dengan urusan daerah.[3] Dalam menjalankan fungsi legislasi, ketiga lembaga tinggi negara tersebut dibatasi oleh UUD 1945 sebagai dasar dari segala peraturan perundang-undangan sekaligus dasar politik hukum Indonesia. Di dalamnya, ada norma hukum fundamental (staatsfundamentalnorm) yang terletak pada bagian pembukaan serta aturan dasar negara (staatsgrundgesetz) yang terletak pada bagian batang tubuh.
Zainal Arifin Mochtar melakukan pembabakan sejarah perpolitikan Indonesia menjadi periode 1945–1959 dengan konfigurasi politik yang demokratis, periode 1959–1966 (Orde Lama) dengan konfigurasi politik yang otoriter, dan periode 1966–1998 (Orde Baru) dengan konfigurasi politik yang otoriter meski sempat didahului oleh masa pendek yang sedikit demokratis. Pada masa Orde Lama, penyimpangan terhadap hukum dilakukan secara kasatmata. Rezim Orde Baru menggunakan cara yang lebih lihai, yakni dengan menggunakan hukum sebagai “senjata” untuk melegitimasi pelbagai program politiknya (autocratic legalism). Setelah Orde Baru runtuh, banyak kalangan yang mengusulkan amendemen UUD 1945 karena dianggap menyediakan “jembatan” bagi penyelewengan kekuasaan. Namun, tidak ada satu pun yang menganggap Pancasila sebagai falsafah negara harus diubah atau bahkan sekadar diperbaiki. Sebaliknya, cita-cita untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma politik hukum makin kuat sehingga setiap produk hukum harus selaras dengan Pancasila. UUD 1945 juga tidak terlepas dari pengaruh tersebut lantaran selain berkedudukan sebagai dasar dari politik hukum, UUD 1945 sendiri juga merupakan produk dari politik hukum.
Produk hukum merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Nasional harus serasi dengan politik hukum pembentukan UU. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (“RPJPN“) Tahun 2005–2025 menghendaki penyempurnaan sistem hukum nasional dengan cara melakukan pembaharuan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi zaman. RPJPN kemudian akan menjadi petunjuk untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (“RPJMN“) bagi presiden dan wakil presiden terpilih. RPJMN adalah kebijakan hukum berupa peraturan presiden (“Perpres“) yang mengaktualisasikan visi dan misi dari presiden dan wakil presiden. Permasalahan utama terkait RPJMN yang disorot oleh Zainal Arifin Mochtar adalah nihilnya mekanisme checks and balances dalam tahapan pembentukan Perpres soal RPJMN sampai implementasinya kelak. Permasalahan lain yang muncul adalah RPJMN dibatasi oleh masa jabatan presiden dan wakil presiden sehingga sulit mengharapkan akan terciptanya kesinambungan Rencana Pembangunan Nasional.
Demi menghasilkan UU yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, maka Pasal 43 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU P3“) menyatakan bahwa setiap RUU harus disertai naskah akademik–kecuali RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“RAPBN“), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu“), serta pencabutan UU.[4] Naskah akademik merupakan kajian hasil kerja sama antara pakar hukum dan pakar bidang keilmuan lain yang berhubungan dengan materi muatan UU. Naskah akademik itu kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan UU sekaligus alat bukti dalam pengujian UU di MK. Naskah akademik berfungsi untuk mencegah metode penjaringan aspirasi yang bersifat top-down (dari atas ke bawah) dan sarat unsur politik. Dengan demikian, suatu RUU tanpa naskah akademik yang memadai atau bahkan tanpa naskah akademik sama sekali akan mengalami cacat formil sejak masa pembentukannya.
Menilik Akibat dari Politik Hukum terhadap Undang-Undang
RUU yang diajukan oleh presiden harus terlebih dahulu disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham“) bertindak sebagai sebagai koordinatornya. Selanjutnya, presiden akan menyerahkan draf RUU tersebut untuk dibahas di parlemen beserta surat Amanat Presiden (“Ampres“) kepada pimpinan DPR. Zainal Arifin Mochtar mengkritisi Ampres yang sering tidak memuat sikap presiden atas RUU yang akan dibahas. Padahal, Ampres sesungguhnya merupakan sesuatu yang dapat dijadikan objek penilaian politik hukum seorang presiden dalam proses pembentukan UU. Tidak adanya sikap presiden dalam Ampres berimplikasi pada tidak jelasnya politik hukum presiden atas draf RUU yang dimaksud sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan pertanggungjawaban.
Sementara itu, RUU yang diajukan oleh DPR atau DPD diusulkan secara tertulis kemudian diputuskan dalam suatu rapat paripurna. Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR itu dapat berupa persetujuan, persetujuan dengan pengubahan, atau penolakan. Apabila RUU itu mendapat persetujuan atau persetujuan dengan pengubahan, maka Badan Legislasi DPR bertindak sebagai koordinator untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan susunan RUU itu kepada presiden untuk dibahas bersama. Politik hukum DPR sendiri dapat dinilai dari Program Legislasi Nasional (“Prolegnas“) yang disusun oleh DPR, DPD, dan pemerintah.
Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit mengatur bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden demi meraih persetujuan bersama. Pasal tersebut memiliki arti bahwa “persetujuan bersama” oleh DPR dan presiden merupakan konsekuensi logis dari “pembahasan bersama” antara keduanya. Menurut Jimly Asshiddiqie, Baik DPR atau pemerintah juga memiliki hak untuk tidak memberikan persetujuan atas suatu RUU. Zainal Arifin Mochtar meneruskan argumen itu dengan menambahkan bahwasanya penolakan terhadap suatu RUU seyogianya disampaikan pada pembicaraan di tingkat I atau tingkat II karena susunan RUU itu sudah tidak memenuhi syarat “persetujuan bersama”.
Dalam proses pembahasan UU, pihak pemerintah diwakilkan oleh menteri yang bertindak atas nama dan untuk presiden. Oleh karena itu, muncul kejanggalan apabila para menteri yang bertindak atas nama presiden memberikan persetujuan tanpa sepengetahuan presiden. Para menteri yang turut terlibat dalam tahapan pembahasan UU semestinya meminta konfirmasi apakah RUU hasil pembahasan masih selaras dengan politik hukum presiden. Jika presiden merasa politik hukumnya masih cocok, maka menteri yang bersangkutan dapat memberikan persetujuan bersama. Sebaliknya, apabila politik hukum presiden tidak menghendaki RUU hasil pembahasan, maka menteri yang bersangkutan tidak boleh memberikan persetujuan atas nama presiden. Tujuannya adalah untuk menjamin presiden akan melakukan pengesahan RUU yang dimaksud menjadi suatu UU.
“Persetujuan bersama” atas susunan RUU kemudian dapat diartikan sebagai pengesahan materiel, sedangkan pengesahan formal dilakukan oleh presiden sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945.[ Akan tetapi, pengesahan formal itu hanya sekadar formalitas belaka karena Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menyatakan RUU itu tetap wajib diundangkan meskipun presiden tidak kunjung mengesahkan RUU itu menjadi UU dalam tempo 30 hari sejak persetujuan bersama dilakukan. Sejumlah pihak beranggapan bahwa persetujuan yang diberikan oleh presiden dalam tahapan pembahasan adalah bentuk hak veto ala Indonesia sehingga presiden tidak boleh lagi menarik persetujuannya pada tahapan pengesahan. Pengaturan ini membawa Saldi Isra berkesimpulan bahwa perubahan UUD 1945 hasil amendemen belum menyentuh bagian fungsi legislasi serta memastikan bahwa Indonesia mempraktikkan sistem presidensial yang tidak murni.
Amendemen UUD 1945 juga ternyata belum mampu menarik garis pembatas yang jelas apakah Indonesia menganut sistem parlemen unikameral, bikameral, atau trikameral. Eksistensi DPD sebagai checks and balances antara DPR dan daerah justru terlihat hanya sebatas memainkan peran figuran saja. Hal tersebut mengakibatkan kepentingan partai politik di DPR menjadi lebih dominan ketimbang kepentingan daerah yang merupakan kompetensi utama DPD. Oleh karena itu, urgensi penguatan kewenangan DPD kian kuat demi eksisnya mekanisme checks and balances terhadap DPR sekaligus menjaga kualitas legislasi dari pengaruh dominasi partai politik yang menduduki kursi di DPR.
Spektrum partai politik di Indonesia pada masa sekarang dapat dibagi menjadi dua, yakni partai politik berhaluan nasionalis dan partai politik berhaluan islamis. Akan tetapi, umumnya seluruh partai politik di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar utama dari aktivitas politik yang mereka tawarkan kepada pemilih. Masalah muncul ketika Pancasila dan konstitusi justru hanya dijadikan basa-basi untuk mendulang suara serta nilai-nilai di dalamnya diabaikan begitu saja demi kepentingan politik. Sistem multipartai yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem politik dengan kemajemukan masyarakat di Indonesia justru menimbulkan paradoks yang mengakibatkan presiden kelabakan ketika mesti berhadapan dengan parlemen yang sarat atas kepentingan partai politik.
Variabel lain yang memengaruhi politik hukum pembentukan UU adalah risalah pembahasan RUU. Risalah pembahasan RUU merupakan salah satu alat yang diperlukan ketika hendak melakukan penafsiran historis terhadap RUU. Risalah ini dapat digunakan untuk melacak maksud awal tujuan pembentuk UU serta bagaimana dinamika politik hukum dalam tahapan pembahasan. Sering kali risalah pembahasan RUU di Indonesia tidak komprehensif dalam memuat substansi yang diperdebatkan sehingga menimbulkan kebingungan dalam upaya menentukan posisi para pembentuk UU. Padahal, hal tersebut sangat penting dalam konteks pengujian UU di MK.
Dalam buku ini, Zainal Arifin Mochtar memberikan gagasan tentang simulasi pemberlakuan UU. Gagasan ini lahir dari perspektif bahwa hukum tertulis (law on the books) tidak selalu sama dengan pengaplikasiannya dalam masyarakat (law in action). Simulasi pemberlakuan UU juga menambah porsi partisipasi publik untuk mengawasi produk hukum yang akan berlaku bagi mereka di kemudian hari sekaligus meminimalisir celah dari suatu UU. Partisipasi publik dalam proses legislasi tidak boleh hanya untuk memenuhi syarat pembentukan peraturan saja, melainkan harus menyentuh esensi dari partisipasi publik itu sendiri. MK sendiri menjabarkan konsep partisipasi yang bermakna (meaningful participation) terdiri atas pemenuhan hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan.
Tahap terakhir dalam proses pembuatan suatu UU adalah tahap pengundangan. Pengundangan sendiri memiliki makna agar setiap orang mengetahui bahwa ada suatu UU sudah berlaku di masyarakat. Jika terjadi suatu pelanggaran, maka harus dilihat kapan suatu UU itu mulai berlaku. Penentuan itu sendiri tidak selalu sama dengan tanggal pengundangannya, bisa saja perlu ada pengunduran karena memerlukan kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.
Dalam pelaksanaan suatu UU itu sendiri, perlu adanya peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagai peraturan pelaksana ketentuan UU. Peraturan pelaksana yang sering kita kenal saat ini adalah Peraturan Pemerintah (“PP”) dan Perpres. Keberadaan kedua peraturan pelaksana itu masih diperlukan sebagai pengimplementasian ketentuan yang masih umum di dalam suatu UU. Sayangnya, penggunaan peraturan pelaksana terhadap suatu UU sering kali tumpang tindih dalam melaksanakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal tersebut membuat harus adanya pembatasan yang jelas mengenai kapan suatu UU memerlukan PP atau Perpres agar tumpang tindih peraturan perundang-undangan tidak terjadi.
Referensi :
- https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/22-artikel-politik-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-daerah.html#:~:text=Menurut%20Mahfud%20MD%20politik%20hukum,dalam%20rangka%20mencapai%20tujuan%20Negara%E2%80%9D.
- https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/